[Book Review] Bukan Pasar Malam, Cerita Sederhana Penyayat Hati
Review Buku
Bukan Pasar Malam karya Pramoedya Ananta Toer
Sosok
Pramoedya Ananta Toer (selanjutnya dipanggil PAT dalam unggahan ini) adalah
penulis yang akrab di telinga saya, terutama karena karya-karyanya sering
dibahas dalam forum pertukaran budaya antara Indonesia dan Tiongkok. Beliau sering disandingkan dengan Luxun,
sastrawan kenamaan dari Tiongkok yang juga telah menerbitkan banyak karya-karya
terkenal.
Entah
bagaimana ceritanya, saya ingat beberapa bulan lalu main ke Gramedia dan
memutuskan “Mau beli novel klasik karya penulis Indonesia!” dan di rak yang
saya lihat, berjejer buku-buku karya PAT.
Seri Tetralogi Buru yang terkenal terpampang jelas di bagian paling
muka, berjejer apik. Jelas, lagipula
siapa sih yang tidak tahu film Bumi Manusia yang kapan hari rilis dan tokohnya
diperankan oleh Iqbal Cowboy Junior?
Anyway, saya memutuskan untuk tidak membeli buku dari
salah satu karya tetrologi tersebut.
Mata saya tertuju kepada salah satu buku dengan ketebalan yang jauh
tipis dibandingkan buku-buku lain.
Judulnya, Bukan Pasar Malam. Oke,
saya beli yang ini.
Sudah lama sekali sejak kali terakhir saya membaca karya yang menggunakan sudut pandang pertama “aku”. Biasanya sih, sudut pandang ini masih umum digunakan oleh penulis-penulis fanfiction di Wattpad. Namun biasanya untuk penulis novel kawakan baik dalam maupun luar negeri, hamper sebagian besar menggunakan sudut pandang ketiga serba-tahu.
Buku ini
mengisahkan “Aku” yang namanya tidak diketahui secara utuh. Dalam buku, ia beberapa kali disapa sebagai
“Gus”. Siapakah ia? Bagus?
Agus? Gustav? Entahlah.
Intinya, ia adalah putra sulung dari sebuah keluarga berukuran besar.
Sosok “aku”
ini sudah berada di perantauan (Jakarta) selama beberapa tahun. Sudah beristri, namun baru mendapatkan pekerjaan
sehingga keadaaan finansialnya tidak begitu bagus. Ia menerima surat dari pamannya di Blora,
memintanya untuk pulang karena kondisi kesehatan ayahnya tidak baik, dengan
pesan tersirat ‘kau harus datang, waktu ayahmu tidak banyak lagi’.
Akhirnya pulang,
membaca diajak menyelami kegundahan yang dialami “aku” sebagai seorang pemuda
berusia 25 tahun yang berhasil hidup melewati perang antara Indonesia dengan
Belanda dan Jepang. Ada kilas balik
mengenai perang, dan kesusahan yang harus dihadapi keluarganya untuk bertahan
hidup.
Kemerdekaan
Indonesia bukan jaminan bahwa seluruh rakyat hidup makmur. Buktinya, ayahnya yang berprofesi sebagai
guru sudah lama tidak menerima gaji.
Adik-adik “aku” berjumlah tujuh orang, ada yang masih kanak-kanak. Adik ketiganya terkena TBC sehingga dalam
keluarga itu, ayah dan putrinya sama-sama tergeletak lemas tak berdaya di atas
kasur.
Rumah
keluarga “aku” sudah tua dan miring.
Keluarga itu sudah kehilangan kakek, nenek, dan ibunya sehingga ketika
ayahnya sakit, rasanya seperti kehilangan pilar penopang. Barulah ketika “aku” pulang, rasanya seperti
air penyejuk dahaga bagi seluruh keluarga.
Mereka tidak hanya bergantung secara finansial kepada “aku”, namun
secara emosional pula.
Inti utama
dalam buku ini ialah bagaimana “aku” menjalani hari-harinya dengan melihat
ayahnya yang makin hari makin sekarat, dipenuhi tanggung jawab dan beban berat
sebagai tulang keluarga yang baru, dan posisinya sebagai anak sulung yang
menjadi batu sandaran bagi seluruh adik-adiknya.
Pertanyaan
terbesar “aku” sepanjang buku ini berpusat pada “Mengapa keluarga kami bisa
jatuh terjerat kemiskinan seperti ini?
Apa yang bisa kulakukan untuk keluargaku? Mengapa rasanya banyak hal yang disembunyikan
oleh Ayah?” Usut punya usut, “aku” baru
bisa mendapatkan seluruh jawaban tersebut setelah ayahnya mangkat. Sosok ayah yang tidak pernah ia pahami,
ternyata adalah nasionalis yang sampai akhir hayatnya menolak jabatan tinggi
yang diberikan oleh Belanda, semata-mata karena ia adalah sosok berintegritas yang
tidak ingin terjebak dalam dunia politik yang penuh kecurangan. Ia mengabdikan diri menjadi guru, dalam usaha
keluarganya mereka berbaik hati mengizinkan warga untuk ngebon; tapi semua itu
tidak menghasilkan balas budi dari teman, kerabat, dan warga desa Blora.
Lantas
mengapa judulnya Bukan Pasar Malam? Ini
menggambarkan situasi di rumah keluarga “aku” sesudah ditinggal mati oleh
ayahnya. Banyak tetangga dan teman yang
datang melayat, dan keramaian tersebut membuat “aku” berkata dalam batinnya
bahwa “Ramai ini bukan pasar malam, namun disebabkan oleh ayahku semata.”
Skor
pribadi saya? 8 dari 10. Buku ini
realistis, dan ini menjadi salah satu daya tariknya. Saya lumayan lelah dengan cerita-cerita yang
memiliki nilai moral ‘kebaikan akan selalu dibalas dengan kebaikan’, ketika
dalam kehidupan nyata, kenyataan tidak
segampang ucapan tersebut. Bagi
orang-orang susah dan miskin, susah untuk bisa hidup keluar dari jerat kemiskinan. Konflik batin yang dialami “aku” sebagai
seorang anak, seorang suami, seorang kakak, dan seorang putra sulung sangat
mengena. Mungkin karena saya anak sulung
juga kali ya? Jadinya bisa lebih relate.
Saya
merekomendasikan buku ini untuk dibaca, hitung-hitung sebagai tambahan bacaan
karya PAT karena karya yang ini tidak sepopuler karyanya yang lain. Kesannya?
Wah intinya sampai sekarang saya jadi overthinking masalah keluarga dan finansial setelah membaca buku
ini, hiks L
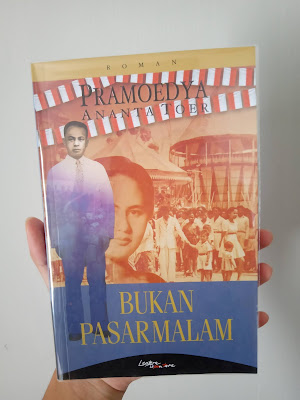


Komentar
Posting Komentar